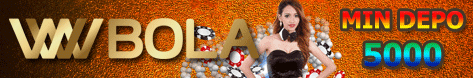Julukan Kampung Zombie bukan sekadar istilah sensasional bagi deretan rumah di kawasan Cililitan, Jakarta Timur. Nama itu lahir dari pemandangan yang nyaris sureal, rumah-rumah yang tampak hidup di lantai atas, sementara bagian bawahnya mati—kosong, gelap, dipenuhi lumpur dan sisa banjir yang tak pernah benar-benar pergi.
Di bantaran sungai itu, kehidupan berjalan seperti makhluk yang bangkit dari genangan. Penghuninya beraktivitas di lantai dua atau tiga rumah, sementara lantai dasar dibiarkan membusuk oleh endapan tanah dan air. Kampung ini sudah lama akrab dengan banjir kiriman dari Bogor, dan dari situlah identitas “zombie” melekat.
Reporter Liputan6.com Siti Khoirul Inayah, yang menyambangi lokasi Kampung Zombie pada Kamis, 7 Januari 2026 sore, tampak melihat bagaimana kontrasnya bangunan langsung terasa. Ada rumah yang ditinggikan hingga beberapa meter, seolah bersiap melawan banjir berikutnya. Di sebelahnya, bangunan lama tampak tenggelam, rendah, dan rapuh. Di beberapa titik, lantai dasar sudah berubah fungsi bukan lagi ruang keluarga, melainkan ruang lumpur.
Di kampung itulah Yudi (50) bertahan. Pedagang bakso cuanki asal Cikarang itu sudah lebih dari setahun mengontrak rumah di Kampung Zombie bersama anaknya. Alasan Yudi sederhana dan klasik, harga sewa.
“Kalau di sini ada yang Rp300 ribu sampai Rp600 ribu per bulan. Saya sendiri Rp400 ribu,” kata Yudi.
Harga murah itu, menurutnya, sebanding dengan risiko. Kontrakan dengan tarif rendah biasanya memiliki kamar mandi di luar rumah, dipakai bersama oleh lima hingga enam keluarga.
“Kalau yang Rp300 ribu sampai Rp400 ribu itu kamar mandinya di luar, jadi kalau mandi harus antre. Yang Rp600 ribu sampai Rp1,2 juta baru kamar mandinya di dalam,” tuturnya.
Yudi pindah ke Cililitan atas saran sesama pedagang. Katanya, Jakarta menjanjikan omzet lebih besar. Namun realitas tak sepenuhnya seindah cerita.
“Penghasilan enggak jauh beda sama di Cikarang. Bedanya, di sini harus siap banjir,” ujarnya lirih.
Banjir Kiriman, Air Bisa Sampai Atap
Banjir di Kampung Zombie bukan datang dari hujan lokal. Ancaman justru muncul ketika hujan deras mengguyur wilayah hulu.
“Kalau hujan di sini mah enggak banjir. Kalau hujan di Bogor, baru banjir,” kata Yudi.
Banjir terparah yang pernah ia alami bahkan mencapai atap rumah. Pada kejadian terakhir, air setinggi dua meter merendam hampir seluruh kawasan.
“Yang kemarin itu dua meter. Kontrakan tempat saya tinggal juga kena,” ujarnya.
Saat banjir besar, warga tak punya banyak pilihan. Mereka mengungsi ke masjid yang posisinya lebih tinggi. Di sanalah seluruh warga berkumpul, tidur beralaskan tikar, menunggu air surut.
“Kalau banjir gede, ngungsinya ke masjid. Semua warga ke sana. Kadang dapat bantuan juga, sembako, ada relawan,” tutur Yudi.
Air biasanya surut dalam tiga hingga lima hari. Namun setelahnya, pekerjaan berat menanti: membersihkan lumpur. Di masa itu, Yudi tak bisa berjualan.
“Kalau banjir gede, enggak bisa jualan. Barang kadang hanyut, harus cari modal lagi,” katanya sambil mengelap peluh.
Kini, warga Kampung Zombie hanya bergantung pada peringatan BMKG yang masuk ke ponsel.
“Kalau masih siaga dua, kami mulai deg-degan. Siaga satu, langsung disuruh ngungsi,” ujar Yudi, mengenang kecemasan yang berulang.
Rumah Ditinggal, Kampung Makin Sunyi
Jumlah penghuni Kampung Zombie terus menyusut. Berdasarkan keterangan warga dan ketua RT yang beredar di media sosial, dari sekitar 23 kartu keluarga, kini hanya tersisa sekitar 13 kartu keluarga.
“Yang lama-lama banyak yang udah pindah. Sekarang kebanyakan pendatang,” kata Yudi.
Banyak rumah ditinggalkan, terutama bagian bawahnya. Lumpur mengering, pintu tertutup rapat, dan jendela kosong menambah kesan sunyi. Inilah yang membuat kampung itu terasa menyeramkan, terutama saat malam tiba.
“Makanya disebut kampung zombie. Rumahnya banyak yang kosong, enggak keurus,” ujarnya.
Pemerintah, kata Yudi, sudah beberapa kali datang melakukan pengukuran untuk rencana relokasi. Namun hingga kini belum ada kepastian.
“Kemarin sering ada yang datang ngukur-ngukur, tapi enggak tahu kapan jadinya,” ungkapnya.
Pompa air baru memang sudah dipasang. Tapi bagi warga, itu belum cukup untuk melawan banjir yang datang berulang kali.
Di tengah ketidakpastian, Yudi memilih bertahan. Murahnya kontrakan masih menjadi alasan utama, meski harus hidup di kampung yang separuh hidup, separuh ditinggalkan.
“Kalau malam lumayan seram. Banyak rumah kosong, gelap. Tapi untung masih ada lampu jalan. Saya sudah biasa pulang malam, lama-lama terbiasa,” katanya.