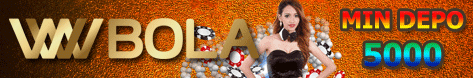Seorang pria paruh baya duduk di atas becak kecil miliknya, bertarung dengan teriknya matahari dan bisingnya angkutan kota. Sesaat ia melirik kendaraan yang berlalu lalang di hadapannya.
Sesekali Warto membandingkan kendaraan berlapis baja itu dengan becak tua miliknya yang sudah berusia puluhan tahun.
Namanya Warto, pengayuh becak tua asal Brebes, Jawa Tengah yang merantau di Depok, Jawa Barat untuk mencari sesuap nasi.
Dia dan becaknya sudah berkawan lama, mengadu nasib di kota orang. Puluhan tahun sudah ia mengayuh becak. Profesinya sebagai tukang becak sudah ia jalankan sejak tahun 1960.
Warto meninggalkan istri dan ketiga anaknya yang masih sekolah di kampung. Namun sayang, Warto tak bisa mengirim uang untuk mereka. Penghasilannya yang tak menentu hanya cukup untuk ia makan sehari-hari, itu pun kadang harus berutang dengan pemilik warung.
Warto juga terpaksa menunggak bayaran sekolah anaknya selama berbulan-bulan karena tak ada uang.
“Ya kalau ada duit bayar, kalau nggak ada duit nunggak,” ucap Warto, ketika diwawancarai Liputan6.com pada Rabu 5 November 2025.
Melihat kondisi Warto, anak-anaknya terkadang tak tega dan meminta Ayahnya untuk pulang. Namun, Warto bersikukuh untuk tetap tinggal di Depok, meski hanya dengan penghasilan Rp 10.000 – Rp 20.000 per hari dan tidur di jalanan.
“Penghasilannya sehari paling saya dorong Rp 10.000,” cerita Warto.
Warto Tak Punya Harta, Hanya Becak Tua yang Dia Anggap Rumah
Warto tak punya apa-apa, ia bertahan di Depok tanpa keluarga, bahkan tanpa rumah. Rumah Warto adalah becak miliknya sendiri. Itulah satu-satunya tempat untuk Warto berteduh dari panas dan hujan.
“Ya, nggak mampu, buat bayar gaada, kan kontrakan kan tiap bulan Rp 800 – Rp 900 ribu,” ucapnya sambil sedikit tertawa, seolah kenestapaan ini sudah menjadi makanan sehari-hari untuknya.
Terkadang, kalau cuaca sedang tak mendukung, Warto harus menumpang tidur di emperan puskemas dekat tempat ia dan becaknya mangkal. Untungnya, pegawai puskesmas tak pernah mepermasalahkan kehadiran Warto.
Di atas becaknya terlihat tumpukan baju yang tak begitu banyak, itu adalah sisa pakaian yang ia miliki. Karena tak punya rumah, Warto terbiasa untuk mandi dan mencuci pakaiannya di Sungai Ciliwung. Bahkan, untuk menjemur pun ia harus menumpang di pagar pembatas rel kereta api.
“Iya sarung, kain, jaket, dibawa. Ntar kalau mau mandi, udah, cuci satu di jemur, udah paranin, ambil, jemur lagi,” kata Warto.
Sehari-hari, warto hanya duduk terdiam di atas becaknya. Menunggu penumpang datang dan mau memakai jasanya. Kini, Warto harus bersaing dengan transportasi modern yang semakin berkembang. Becak warto mati tergerus zaman.
“Udah mati, becak nggak ada yang naik. Anak sekolah, orang belanja biasanya kan dulu banyak, orang ke pasar naik becak. Sekarang nggak ada sama sekali, Ini sendirian saya,” ungkap Warto.
Tak hanya berhadapan dengan kerasnya kehidupan di kota, Warto kadang masih harus menerima omelan-omelan kecil dari istrinya. Namun, bagi Warto yang terpenting hari ini dia masih bisa hidup dengan umur panjang dan badan yang sehat. Dia mensyukuri segala nikmat kecil yang Tuhan beri untuknya.
“Saya kadang-kadang kalau istri ngomel ya udah lah, semakin disyukuri, sehat ya Alhamdulillah,” ujarnya.
Menahan Sakit dan Rindu Puluhan Tahun Karena Tak Punya Uang untuk Pulang
Warto tetaplah seorang Ayah yang merindukan keluarganya nan jauh di sana. Sekeras-kerasnya ia bertahan, ada rasa rindu yang ia pendam dalam diam.
Warto menunduk sedih, suara kecil hatinya menggema, rasanya ingin sekali bertemu dengan anak-anaknya di kampung. Namun apa daya, untuk makan sehari-hari saja Warto tak mencukupi.
Warto punya mimpi besar yang mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang kecil. Kalau bisa memilih takdir, Warto hanya ingin jadi petani di kampungnya. Katanya, ia ingin hidup damai di kampung dan tak mau terpisah jauh lagi dari anak dan istri.
“Saya kadang-kadang sedih. Kalau ada duit, saya mau pulang ke kampung, mendingan bekerja di kampung, pas ke sini, enggak ada apa-apa,” lirihnya.
Pria paruh baya ini sudah kebal dengan rasa sakit. Terbiasa bermalam di atas becak membuatnya tak lagi mengeluh. Panas dan hujan ia hadapi bersama becak kesayangannya. Menurutnya, pulang ke kampung pun percuma kalau ia tak bisa membawa apa-apa untuk anak dan istrinya.
“Sehari-hari sampai badannya sakit, angin-anginan, tapi ya mau pulang udah tanggung, enggak punya duit ya,” cetus Warto.
Warto tak mampu untuk membayar dokter. Kalau dirasa sudah tak sanggup menahan rasa sakit, Warto biasanya hanya bertahan dengan minum obat warungan. Lalu, ia kembali terlelap tidur, beristirahat di atas becak mungilnya sampai keadaan tubuhnya cukup membaik.
“Kalau udah pala puyeng, beli bodrex, udah sembuh. Beli Bodrex, minum,” kata Warto.
Di Tengah Kesulitan, Warto Tetap Memperjuangkan Pendidikan Untuk Anaknya
Nasib malang Warto cukup ia nikmati sendiri. Warto tak ingin anak-anaknya kelak merasakan hal yang sama. Sesulit apa pun Warto di tanah rantau, ia selalu berupaya agar anak-anaknya tetap bisa merasakan akses pendidikan yang layak.
“Jangan sampai nasibnya sama kayak Bapak, jadi tukang kuli. Kamu kalau takut nggak bayar (sekolah), tenang aja, saya pasti bayar,” kata Warto.
Kelak ketika anak-anaknya beranjak dewasa, Warto berharap mereka tak perlu pergi jauh dari kampung halaman seperti Warto. Warto tak mau nasib anaknya berujung pahit di kota orang. Dia hanya ingin anaknya hidup layak dan berkecukupan di kampung.
“Ngerantau di sini nggak boleh. Di sini udah nggak ada apa-apanya,” cerita Warto.
Warto tak marah atas takdir yang ia jalani saat ini. Dengan lapang, ia menerima semua ketetapan tuhan. Di atas becak kecilnya, ia masih bisa memberi senyuman untuk orang-orang di sekitarnya. Puluhan tahun ditempa dengan berbagai cobaan, kini Warto sudah berdamai dengan hidupnya sendiri.
“Boleh disyukuri, saya titip sama Yang Kuasa, saya sehat, lancar, gitu aja,” pungkas Warto.